PUNGGAWANEWS – Pada 2 September 1997, dua hari setelah kematian tragis Putri Diana, aktor George Clooney berdiri dan menyampaikan pernyataan yang tajam dan tak terbantahkan: “Princess Di is dead. And who should we see about that? The driver of the car? The paparazzi? Or the magazines and papers who purchase these pictures and make bounty hunters out of photographers?”
Clooney menolak diam ketika media tabloid bersembunyi di balik retorika kebebasan pers, sembari menghindari tanggung jawab moral. “Saya ingin adil kepada sang putri,” katanya, “tapi semakin saya mendengar para editor menghindar, saya tahu satu-satunya hal yang adil adalah berdiri dan mengatakan ini dengan jelas.” Pidato itu bukan hanya respons emosional atas tragedi, tapi sebuah peringatan keras bahwa perburuan gambar telah melampaui batas, yang menjadikan ruang publik sebagai ladang tanpa etika.
Lebih dari dua dekade kemudian, perburuan itu masih berlangsung, hanya bentuknya yang berubah. Di era digital hari ini, kita hidup dalam paradoks kebebasan: ingin eksis, harus rela privasi terkikis. Ingin aman, terpaksa mundur dari ruang publik. Tapi di balik ledakan konten dari kamera dan ponsel, ada sesuatu yang pelan-pelan menghilang yaitu etika.
Pagi di Jalan Pettarani, Makassar. Lalu lintas padat, orang berolahraga, petugas menyapu jalanan. Tapi yang lebih nyaring adalah klik kamera, banyak dari mereka yang sedang beraktivitas biasa, tiba-tiba muncul di media sosial orang asing, tanpa izin. Dengan tagar seperti #MorningRun atau #PettaraniVibes, wajah-wajah itu menjadi konten.
Alasannya sederhana: “Kan ini ruang publik.”
Ruang publik bukan ruang tanpa aturan. Bukan zona bebas moral. Siapa pun yang berada di trotoar, taman, atau jalanan, tetap memiliki hak atas dirinya sendiri, termasuk hak untuk tidak direkam, tidak diunggah, dan tidak dimanipulasi.
Kita sering lupa, visual juga data, layaknya data pribadi lainnya, potret seseorang bisa disalahgunakan. Kasus foto diam-diam yang digunakan untuk iklan atau penipuan berbasis AI semakin marak. Bukan hanya artis atau tokoh publik yang jadi korban, orang biasa pun bisa.Lalu, apakah berarti tak boleh memotret di ruang publik? Boleh. Tapi gunakan etika.
Wartawan saja yang memang pekerjaannya merekam, kenyataannya juga dibekali kode etik. Dalam Buku Saku Wartawan 2024 dari Dewan Pers, disebutkan pentingnya meminta izin saat memotret orang, bahkan di tempat terbuka.
Masalahnya, masyarakat hari ini berubah jadi jurnalis dadakan. Semua orang bisa jadi content creator. Sayangnya, tidak semua dibekali pemahaman. Tidak ada pelatihan. Tidak ada batas. Maka timbul pertanyaan penting: siapa yang menyusun “buku saku” untuk mereka?
Secara hukum, sebenarnya sudah ada pondasi, yaitu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa pengambilan data visual di ruang publik hanya sah dalam konteks tertentu: keamanan, bencana, atau lalu lintas. Pasal-pasalnya mengatur hak warga untuk tahu, menyanggah, bahkan menghapus data visual jika merasa dirugikan.
Namun hukum hanya menjadi batas minimum. Untuk menjaga martabat manusia, kita butuh sesuatu yang lebih dari legalitas: kita butuh budaya etis.
Budaya itu dibangun lewat komunikasi, lewat rasa hormat.
Sebagai praktisi komunikasi, Penulis percaya bahwa interaksi publik yang sehat bertumpu pada kesadaran bahwa setiap wajah yang kita temui adalah pribadi, bukan objek konten.
Maka ketika memotret di jalan, tanya dulu. “Pak, boleh saya ambil gambar?” “Bu, kalau saya unggah ini, tidak apa-apa?”
Penelitian oleh Candra Febry Adianto dari UPN Veteran Jakarta (2024) menunjukkan bahwa etika adalah jembatan penting antara fotografer jalanan dan objeknya. Tanpa komunikasi, visual bisa berubah menjadi kekerasan simbolik. Bukannya mendokumentasi, malah merendahkan.
Filsuf Jürgen Habermas sudah mengingatkan kita soal ini sejak lama. Dalam The Theory of Communicative Action, ia menyebut bahwa komunikasi sejati harus dilandasi kesepahaman bersama, bukan pemaksaan sepihak. Dalam konteks hari ini, itu berarti: jangan ambil foto tanpa persetujuan. Jangan unggah tanpa empati.
Lalu apa yang bisa dilakukan?
Pertama, kita butuh literasi digital yang lebih etis. Sekolah, komunitas, dan pembuat konten harus dilatih bukan hanya soal cara membuat konten, tapi juga bagaimana memahami dampaknya. Pendidikan selama ini terlalu fokus pada teknis. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah sensitivitas sosial: bahwa wajah di kamera adalah manusia, bukan materi viral.
Kedua, sudah waktunya komunitas menyusun Kode Etik Fotografi Jalanan. Kota seperti Makassar sering jadi panggung kegiatan publik: lari pagi, konser, festival. Dokumentasi visual selalu ada, tapi jarang ada panduan etikanya. Kode etik ini bukan soal pelarangan, tapi penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Komunitas bisa menyepakati titik kumpul atau jadwal latihan. Mengapa tidak menyepakati pula batas etis saat mengabadikan orang?
Di dunia digital, kita semua adalah warga. Dan setiap warga punya tanggung jawab membangun norma bersama. Maka, mari kita tetapkan satu protokol utama dalam bermedia sosial, yaitu hormati orang sebelum membagikan wajahnya.
Adekamwa – Humas Pusjar SKMP LAN

















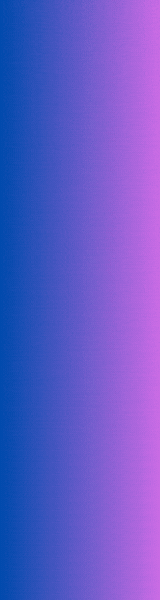

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.